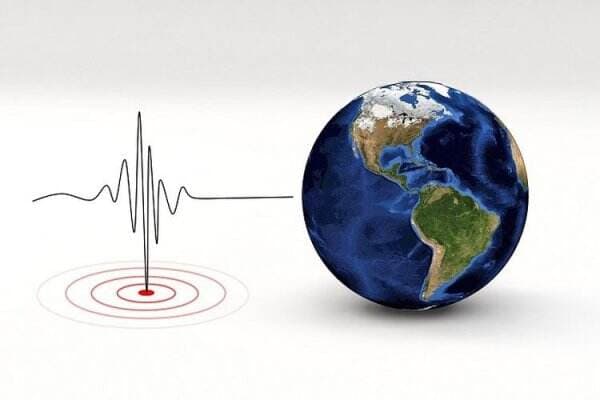Dari Ayat-Ayat Cinta ke Dawsons Creek: Jalan Ninja Kecakapan Seorang Pengarang
SEKAR MAYANG Editor dan pengulas buku, hidup di Bali
AMAT menarik jika kita mengamati fluktuasi dalam dunia literasi, khususnya fiksi. Baru-baru saja, seorang pengarang yang cukup punya nama (dan pasar) habis-habisan dirujak banyak orang. Tentunya orang-orang ini telah lebih dahulu membaca karya-karya si pengarang.
Kang Abik, begitulah nama pendek Habirurrahman El Shirazy, pengarang yang mendapat kritikan atas karya terbarunya yang berjudul Api Tauhid . Hanya saja, bukan netizen yang budiman jika kritikan tidak merambat ke mana-mana.
Adalah Ayat-Ayat Cinta yang dijadikan bahan rujakan warganet penikmat fiksi. Ya, saya tidak hendak menambah daftar panjang kritikan terhadap karya beliau sebab saya pun belum membacanya. Saya hanya ingin sedikit berbagi pemikiran mengapa seorang pengarang bisa terjebak memakai pola yang sama berulang kali.
Ada sebuah saran yang sepertinya lazim diketahui orang-orang di komunitas fiksi , atau yang baru belajar menulis fiksi. Tulislah apa yang kamu ketahui. Atau, tulislah apa yang ingin kamu ketahui. Dua kalimat itu tentu punya makna yang berbeda.
Kalimat pertama terlihat lebih mudah dikerjakan. Kita hanya diminta menulis apa yang benar-benar sudah kita ketahui sebelumnya. Tidak perlu riset berat. Hanya butuh mengingat-ingat wawasan apa yang sudah kita punya. Kalimat kedua membutuhkan aksi yang sedikit berbeda. Semisal ingin menulis tentang astronomi namun belum paham banyak hal tentang tema itu, tentu saja kita harus meluangkan waktu untuk belajar lagi.
Saya rasa jika ada tuduhan kurang riset dilayangkan kepada seorang pengarang, itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga bukan berarti aman-aman saja. Riset sangat diperlukan, meskipun kita mengklaim bahwa kita menguasai tema tersebut.
Kapasitas memori manusia amat terbatas. Ada kalanya kita melewatkan sebuah detail kecil namun krusial. Riset juga membuat sudut pandang kita meluas. Kita bisa memberi narasi dari perspektif yang berbeda. Atau yang lebih jauh lagi, kita mungkin akan mendapat tema baru untuk dibahas.
Kenapa Harvey Moeis dan Helena Lim Pakai Rompi Tahanan Warna Pink dan Bukan Oranye? Ini Artinya
Hanya menulis apa yang kita ketahui membuat kita berada di dalam pagar. Gerak kita amat terbatas. Memang, detail bisa dimodifikasi, tetapi tidak dengan pola. Mengapa pola bisa terlacak? Ya, karena kolamnya hanya satu. Tiap hari berenang di tempat yang sama, tentu gerakannya terekam begitu saja di bawah sadar. Ditambah lagi ekosistem yang tidak berubah, atau malah kita yang menolak berubah karena telanjur terbuai kenyamanan semu.
Sementara itu, ketika kita menulis apa yang ingin kita ketahui, jelas akan membuka pikiran lebih luas lagi. Semesta ini tidak terbatasanggaplah begitu. Jadi, mengapa kita tidak mencoba menjelajah lebih jauh? Saya belum lupa rasanya ketika menemukan hal-hal baru yang menarik minat saya saat melakukan sebuah riset.
Yang menarik lagi jika kita membahas gairah seorang pengarang. Rata-rata pengarang menciptakan karakter dari sosok yang ada di dekat mereka. Bisa dari teman, orang tua, anak, rekan kerja di kantor, atau yang paling sering diambil adalah diri sendiri.
Kevin Williamson, pengarang serial Dawsons Creek , mengaku membagi-bagi kepribadiannya untuk tokoh-tokoh ciptaannya. Osamu Dazai kerap menulis tentang keinginan bunuh diri. Ya, karena memang itulah yang dialaminya, di samping budaya itu memang menjadi semacam trademark di Jepang. Siapa lagi yang bisa dijadikan contoh? Pram? Tentu saja ia menulis apa yang ada di sekelilingnya, termasuk memakai kisah dirinya sendiri (serta keluarganya) sebagai bahan.
Nah, jika tidak hati-hati, bahkan identitas terdalam pun bisa muncul ke permukaan. Soal fetish misalnya, tentang bentuk keminatan seksual. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Tanpa sadar, saya banyak menciptakan karakter pria dewasa yang piawai bermain gitar. Tidak peduli level ketampanannya, keahlian bermain gitar itu semacam meningkatkan nilai diri si tokoh. Mengapa? Ya, karena di mata saya, pria yang piawai bermain gitar itu sangat seksi dan menawan.
Dan, jika itu perempuan, seringnya saya akan membuat ia menggemari buku, kopi, dan/atau musik. Mengapa? Ya, karena saya bisa menjelaskan panjang lebar soal sensasi fisik dan non fisik ketika si tokoh berkelindan dengan tiga hal tersebut. Toh memang saya mengalaminya.
Jiwa Atmaja, dalam bukunya Kritik Sastra Kiri , membeberkan perihal kaitan sebuah karya dan identitas penulisnya. Dijelaskan di sana bahwa sebuah karya mampu menyingkap identitas penulisnya, bahkan jenis komunitas tempat si penulis tinggal. Identitas di sini cakupannya luas. Bisa tentang ideologinya, prinsip ekonomi yang dipegang, kepercayaan terhadap agama atau spiritualisme, dan termasuk soal fetish tadi.
Lantas, mengapa seorang pengarang tidak total mengarang saja tentang semuanya? Membuat karakter-karakter yang benar-benar fiktif, yang sama sekali tidak terhubung dengan dirinya, yang sama sekali bertolak belakang dengan kepribadiannya, dan bahkan dengan lingkungan tempat ia tinggal. Tentu saja bisa. Namun, pembaca yang jeli akan mampu menangkap kepura-puraan dan kekosongan rasa dalam karyanya. Ini seperti menikmati karya Vincent van Gogh dalam bentuk fotokopian. Tidak hanya hambar, tetapi juga absurd.
Akan tetapi, absurditas juga bisa lahir dari pola yang terulang tanpa sadar. Memang, tidak ada kebaruan di semesta ini. Semuanya sudah ada sejak awal. Hanya saja, semesta juga memiliki probabilitas yang tak terbatas. Mengapa kita tidak mencoba-coba bermain-main dengan komposisi baru? Takut ditinggal penggemar?
Well , tiap individu punya momennya masing-masing. Ada masanya mereka menggilai fiksi campur aduk, bahkan yang absurd sekali pun. Berikutnya akan beralih ke fiksi yang agak teratur dengan bobot pesan moral yang lebih berat. Berikutnya lagi akan beralih ke non fiksi seperti esai-esai yang ditulis orang lain dengan berbagai tema. Lagi pula, bukankah bahan bakar paling baik untuk seorang pengarang adalah karya tulis non fiksi?
Saya agak mengalami kesulitan ketika harus betulan mengarang sosok imajiner. Mulai dari merancang karakternya, gesturnya, bahkan cara bicaranya, meskipun itu untuk sebuah karya tulis berbentuk cerita pendek. Bayangkan saja jika saya harus melakukannya untuk sebuah karya audio visual.
Tentu saja bukannya tidak bisa, tetapi jelas butuh usaha ekstra memikirkan segala detail agar tidak menimbulkan ketimpangan logika. Akan sangat terbantu jika sebelumnya saya banyak membaca buku mengenai psikologi dan antropologi. Ditambah riset ini dan itu, tentu menciptakan sosok imajiner tidak begitu sulit.
Pasti akan ada sedikit dari diri saya yang ikut lebur dalam sosok itu, tetapi tidak akan lebih menonjol ketimbang kepribadian hasil karangan. Dan, bicara soal logika dalam sebuah karya fiksi, ini akan memakan tempat yang cukup banyak juga. Mungkin di lain kesempatan akan saya buatkan artikel tersendiri.
Yang jelas, menjadi seorang pengarang berarti memegang dua sisi uang koin. Satu sisi, apa yang kita tulis ternyata mampu membuka identitas kita sebagai individu dalam sebuah masyarakat. Dan, di sisi lain, seorang pengarang tetap bisa bersembunyi di balik topeng, Itu hanya fiksi, kok.
Sekian.
Denpasar, 15 Maret 2024