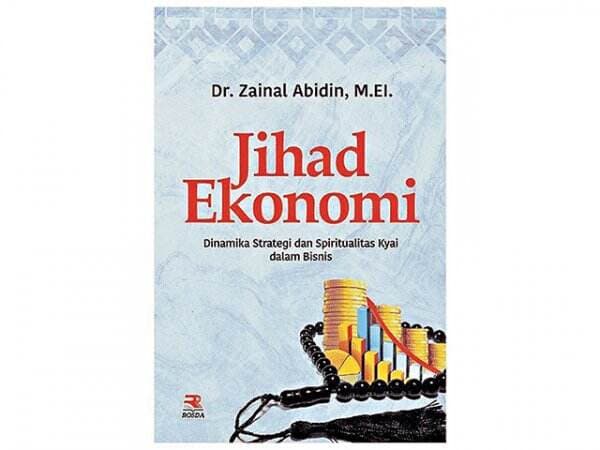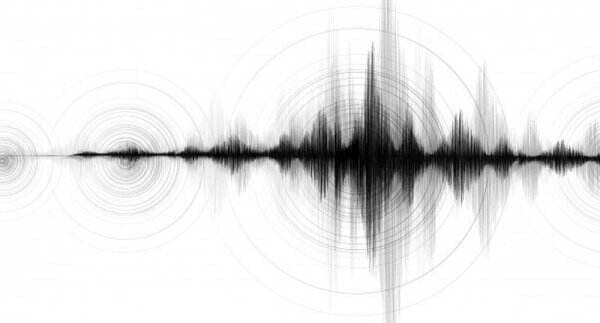Jalan Ekonomi Kiai Kampung
Buku ini tak berposisi menjustifikasi label sekularisasi dan/atau islamisasi. Zainal Abidin berangkat dari titik yang lebih membumi: tengara pada sosok kiai.
ZAINAL Abidin berikhtiar meluaskan makna jihad yang kadung menyempit. Jihad tak melulu berasosiasi berperang fi sabilillah di medan laga. Medan jihad membentang pula pada perbaikan kesejahteraan menyangkut hajat hidup banyak orang, yakni: bidang ekonomi umat.
Dalam bab awal, pembaca seakan-akan dipecut terhadap paradoks antara agama dan ekonomi. Pemisahan keduanya yang sering disebut sekularisasi ini nyatanya kerap menghilirkan ketimpangan sosial-ekonomi amat tajam.
Buku ini menelusuri sebab musababnya dan tak berposisi menjustifikasi label sekularisasi dan/atau islamisasi. Islamisasi, yang di hari-hari ini telah banyak produk undang-undang yang menitikberatkan simbolisasi term agama pada diksi perbankan syariah, misalnya. Titik poin buku tidak membincang sarana dan prasarana syariah yang telah terlembagakan tersebut walau tampak kurang menjejak di masyarakat/umat.
Karena itu, Zainal Abidin menguar titik berangkat yang lebih membumi. Yakni, tengara pada sosok kiai.
Sebagai pemimpin umat, atau mereka yang mengasuh pesantren, kiai adalah manifesto gerak santri dan masyarakat sekitar pesantren babakan laku keberagamaan. Labelisasi kiai semacam ini memang benar adanya, tapi menurut Zainal, semestinya tidak berhenti di satu titik tersebut. Peran kiai idealnya melebar pula pada urusan pemberdayaan ekonomi.
Ditilik mendalam, teks-teks keagamaan yang dikaji para santri menyinggung banyak hal seputar laku perekonomian. Kitabul mal alias pembahasan seputar tata kelola harta benda adalah sejumput kajian yang diajarkan di pesantren melalui pelajaran fikih, tarikh, tasawuf, dan sebagainya.
Hanya, kalangan santri dicukupkan pada lingkup pengetahuan/teori tanpa praktik lapangan. Pun, oleh tokoh sentral pesantren itu sendiri; tak banyak kiai keluar pesantren sejenak menjadi aktor kegiatan ekonomi.
Perspektif sosok kiai di sini bukanlah ustad atau syekh seperti citra yang lalu-lalang di layar kaca/familier. Selain tinggal di pedesaan, sejumlah kiai yang diteliti sekadar berpunya usaha bisnis cakupan kecil-menengah.
Tidak sampai pada usaha besar yang berpunya ratusan karyawan dan omzet hingga miliaran rupiah. Dalam manajerial waktu, para kiai ini tidak lantas pula terbawa dalam arus totalitas berbisnis. Justru, mereka tetap sanggup istiqamah menjalankan kehidupan spiritualitas dan keilmuan di pesantren; meskipun tentunya tidak sesemaksimal andaikata tidak berpunya usaha-bisnis.
Peran kiai, ajengan, buya, dalam kultur masyarakat Indonesia, bisa dimasukkan sebagai agen perubahan sosial. Pengaruhnya amat besar dalam kemudi wilayah sosial-budaya; tapi tidak banyak yang sampai pada skop perekonomian.
Buku ini mengenalkan kiai sebagai antitesis. Tidak lagi tercitra personal berilmu agama tinggi an sich, melainkan meluas sebagai pengusaha, pebisnis, bos. Wedaran kala kiai merupakan pebisnis menujukan argumen senyatanya urusan ukhrawi dan duniawi toh bisa melebur guna saling menopang.
Spiritualitas Bisnis
Buku ini secara khusus memotret sosok kiai beserta pesantrennya di Pamekasan, Madura. Kiai, lebih-lebih pada masyarakat Madura, berkedudukan istimewa.
Buku hasil penelitian lapangan oleh Zainal ini memfokuskan para kiai yang berperan ganda. Tidak saja sebagai layaknya kiai pada umumnya, duduk menjadi pengasuh/pemimpin pesantren, melainkan pula duduk di kursi atasan berpunya karyawan. Peran ganda pada sang kiai ini, selain masih dianggap janggal, juga menurutkan pertanyaan: seberapa kuat tautan relasi agama yang sakral berjumpa dengan profanitas ekonomi.
Tautan agama vis-a-vis ekonomi modern telah berlangsung lama. Secara khusus, pembaca mengenal tesis Max Weber perihal teori nilai lewat bukunya, The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism.
Bagi Weber, ada keterkaitan erat faktor religiusitas pada aktivitas perekonomian. Oleh Zainal, keduanya tidak perlu untuk dihadap-hadapkan, saling menegasikan. Lantaran, agama nyatanya bisa masuk dan menjiwai pada etos dan etis praktik berbisnis.
Laku ekonomi-bisnis yang tidak dicampuri spiritualitas teranggap rawan eksploitasi kepada alam dan manusia/pekerja sebagai modal kapital. Agama dipandang memberikan injeksi spiritualitas yang mewujud pada memanusiawikan karyawan dan bijak pada sumber daya alam. Pertanyaannya: Sanggupkah sosok kiai yang berilmu agama tinggi mengejawantahkan laku spiritualitasnya pada manajerial praktik usaha/bisnisnya?
Atau, malahan predikat kiai berpotensi disalahgunakan untuk mengeksploitasi karyawan dan dalil pembenaran perusakan alam? Pada akhirnya, Zainal membabar bahwa interaksi agama dan ekonomi pada peran ganda sosok kiai ini bisa berjalan selaras-harmonis meski tetap menampakkan banyak kekurangan di sana-sini.
Dan, Zainal tak lupa menambal kekurangan-kekurangan tersebut dengan cukup baik. Dengan kata lain, Zainal mafhum bahwa tidak sedikit peran ganda kiai ini kurang berjalan seimbang; dengan kesibukan ekstra sang kiai mengurus usaha bisnisnya, melupakan pengajiannya.
Rampung membaca buku, ada pesan amat eksplisit kepada umat/masyarakat. Yakni, sesegera mungkin menibakan paradigma penting dan urgen untuk berbisnis alias berwirausaha. Plus, menganggap term ekonomi sebagai sebuah hal yang mesti dipelajari dan dipraktikkan; bukan ditinggal. Ekonomi merupakan salah satu topangan hidup untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Ekonomi idealnya didudukkan pada terma yang sama dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu agama sekalipun. Antipati terhadap ekonomi serta praktik berwirausaha sebagai hal yang di luar urusan agama; anggapan demikian ini hanya akan menjadikan kesejahteraan umat menjadi sulit tercapai. (*)
*) MUHAMMAD ITSBATUN NAJIH , Bergiat di Muria Pustaka, Kudus