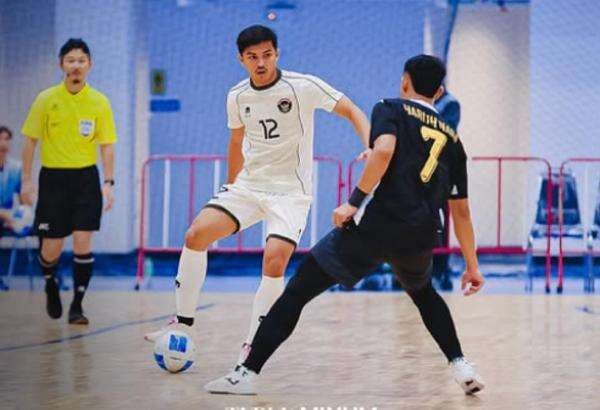Film, Agama, dan Negara: Pertarungan Makna di Ruang Gelap Bioskop
Gilang Ramadan Sub Komisi Litbang Lembaga Sensor Film RIAlumni CRCS UGM
FILM bertema agama tidak dapat direduksi hanya sebagai medium hiburan semata. Ia, dalam konteks tertentu, berfungsi sebagai arena sosial di mana nilai keagamaan, norma moral, dan persepsi publik bertemu, saling berinteraksi, bahkan saling menguji.
Dalam kerangka ini, film agama dapat dipandang sebagai teks budaya yang membuka ruang bagi negosiasi makna sekaligus menjadi refleksi atas dinamika sosial-keagamaan di masyarakat. Ketika sebuah film mengangkat judul atau latar yang menyinggung keyakinan mapan, respons masyarakat muncul dalam bentuk yang beragam.
Sebagian audiens menekankan dimensi moral-religius, sebagian lain menilainya melalui parameter estetika, dan tidak sedikit yang memaknainya sebagai provokasi ataupun pemicu refleksi kritis. Pola respons yang berlapis ini adalah bagian dari sederet bukti bahwa film agama bekerja bukan hanya pada ranah representasi.
Lebih jauh, meminjam istilah Birgit Meyer, film juga bekerja pada ranah performatif (Meyer, 2015). Ia memengaruhi cara publik menafsirkan agama, moral, dan nilai sosial. Film bertema agama, dengan demikian menempati posisi strategis terutama dalam studi tentang agama dan masyarakat. Ia menghadirkan ruang negosiasi di mana norma-norma keagamaan tidak hanya direproduksi, tetapi juga dipertanyakan dan ditransformasikan. Pertemuan antara narasi sinematik dan pengalaman kolektif penonton memperlihatkan bahwa film berperan sebagai ritual sekular, yakni medium yang memungkinkan publik menegosiasikan keyakinan, menafsirkan ulang moralitas, serta merespons dinamika sosial-keagamaan kontemporer secara terpisah.
Performativitas, Kolektivitas, dan Respons Agama Berkaitan dengan ritual sekular tersebut, Catherine Bell, dalam karya seminalnya Ritual Theory, Ritual Practice (1992), mengemukakan bahwa ritualisasi adalah strategi sosial yang terstruktur dan bermakna. Bell menyebut “ritualization as a culturally strategic way of acting,” yang berarti bahwa praktik ritual tidak hanya merupakan tindakan simbolis, tetapi juga merupakan cara strategis dalam bertindak dalam konteks sosial tertentu (Bell, 1992, p. 8).
Ritual, bagi Bell, bukanlah aktivitas yang terisolasi, melainkan bagian dari aktivitas sosial yang lebih luas. Ia berfungsi untuk membentuk dan menegosiasikan makna tentang sesuatu dalam masyarakat.
Dalam konteks film bertema agama, ritualisasi dapat diamati melalui cara film membentuk pengalaman kolektif penonton. Melalui struktur naratif, simbolisme, dan karakterisasi, Bell menyebut bahwa film bertema agama seringkali berfungsi lebih dari sekadar penyampai cerita. Di Indonesia, film seperti Munkar, yang mengambil latar pesantren dengan nuansa horor, dan Kiblat, yang mengangkat konflik spiritual dan otoritas moral, adalah beberapa contoh tentang bagaimana narasi sinematik dapat menghadirkan ketegangan moral dan religius.
Di hadapan penonton yang cenderung religius, film-film ini seolah memaksa mereka berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang nilai keagamaan: bagaimana otoritas moral dijalankan, bagaimana simbol agama ditafsirkan, dan sejauh mana norma-norma religius mampu bertahan menghadapi kompleksitas sosial kontemporer. Seperti halnya ritual, film juga mengaktifkan performativitas kolektif. Respons penonton, baik berupa ketegangan, ketakutan, tawa, maupun diskusi setelah menonton, dapat dibaca sebagai bentuk negosiasi sosial terhadap nilai agama yang ditampilkan di layar. Dalam kasus Kiblat, konflik antara Ainun dan otoritas moral di padepokan menghasilkan interpretasi yang beragam. Ada yang menilainya sebagai kritik atas penyimpangan ajaran, ada yang membacanya sebagai representasi dilema moral universal, dan ada pula yang menanggapinya secara emosional karena simbol keagamaan dipahami secara literal.
Fenomena ini jika ditelisik memakai kerangka Bell, secara tidak langsung, menegaskan bahwa film agama bekerja tidak semata sebagai representasi naratif, melainkan sebagai praktik sosial yang mengaktifkan negosiasi norma dan refleksi kolektif (Bell, 1992, p. 196). Ia membuka ruang bagi publik untuk menafsirkan ulang moralitas, menguji ketahanan nilai-nilai agama, serta menegosiasikan batas antara ekspresi artistik dan sensitivitas religius. Film agama, dengan kata lain, dapat dipahami sebagai arena ritual sekular yang secara aktif memperantarai ketegangan antara agama, moralitas, dan masyarakat.
Dinamika Regulasi Film Judul dan tema yang menantang norma keagamaan dalam film sering kali bersinggungan dengan regulasi, khususnya melalui kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF). LSF bertugas memastikan film tidak menimbulkan keresahan sosial, termasuk dalam hal sensitivitas publik terhadap isu agama.
Namun, kontroversi yang muncul pada film Munkar maupun Kiblat menunjukkan bahwa perdebatan tidak semata lahir dari pelanggaran literal terhadap norma agama. Lebih dari itu, ia hadir dari ketegangan antara kreativitas artistik dan standar moral masyarakat yang dibingkai melalui regulasi.
Respons publik terhadap dua film tersebut adalah bagian dari bukti yang mencerminkan tentang bagaimana regulasi tidak bisa dipahami sekadar sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai arena negosiasi sosial. Bagi sebagian masyarakat, film yang menampilkan paradoks moral atau tafsir keagamaan yang tidak lazim dipandang sebagai bentuk gangguan. Namun, bagi yang lain, film justru membuka ruang refleksi dan kritik sosial. Dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Stuart Hall menegaskan bahwa representasi adalah proses aktif yang membentuk cara pandang terhadap realitas sosial (Hall, 1997). Artinya, dalam konteks film, ia menghadirkan agama sekaligus membangun makna keagamaan melalui bahasa visual, narasi, dan simbol yang digunakan.
Regulasi sensor berfungsi mengontrol konten serta menetapkan batas wacana yang dianggap sah di ruang publik. Hall mengaksentuasikan bahwa regulasi selalu terkait dengan otoritas: siapa yang memiliki hak untuk bersuara, konten apa yang dapat ditampilkan, dan bagaimana batas diskursif ditentukan.
Regulasi tidak berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup norma sosial dan praktik institusional (Hall, 1997, p. 4). Dalam kapasitas itu, LSF berperan sebagai penjaga moral publik sekaligus sebagai aktor budaya yang ikut membentuk arah diskursus agama dalam perfilman nasional.
Problemnya muncul ketika regulasi dihadapkan pada dua tuntutan yang sama-sama penting: menjaga sensitivitas masyarakat terhadap isu agama dan membuka ruang refleksi kritis yang ditawarkan film. Kondisi ini memperlihatkan bahwa film dapat dipahami lebih dari hiburan. Ia bekerja sebagai ritual sekular, meminjam konsep Bell, yang memungkinkan nilai-nilai keagamaan dipertanyakan, diperdebatkan, dan dinegosiasikan.
Film sebagai Ruang Negosiasi Sosial-Religius Film-film kontroversial seperti di atas menegaskan bahwa perdebatan publik merupakan bagian dari ritual sekular itu sendiri. Pola adegan, ritme naratif, dan keterlibatan penonton membentuk pengalaman kolektif yang merefleksikan ketegangan sosial dan religius. Alih-alih semata provokasi, film yang dinilai sensitif justru memicu refleksi kritis tentang batas ekspresi, interpretasi moral, serta dinamika norma keagamaan di masyarakat. Dalam kerangka ini, film berfungsi sebagai barometer sosial-religius, yaitu memperlihatkan sejauh mana publik mampu menegosiasikan nilai, merespons inovasi naratif, dan memproses konflik spiritual secara kolektif.
Memahami film sebagai ritual sekular membuka ruang untuk menilai interaksi antara media, publik, dan norma keagamaan secara lebih mendalam. Kontroversi yang muncul tidak hanya terkait isi cerita, tetapi juga cara penonton memaknai dan menegosiasikan representasi agama dalam ruang publik.
Dari perspektif ini, Munkar dan Kiblat bukan sekadar contoh film provokatif, melainkan arena di mana ketegangan moral dan religius diuji, dibicarakan, dan bahkan dipertanyakan ulang dalam bingkai pengalaman kolektif. Kondisi ini, bagi lembaga seperti Lembaga Sensor Film (LSF), menghadirkan dilema kritis.
Di satu sisi, LSF bertugas menjaga sensitivitas publik dan memastikan agar representasi agama tidak melukai keyakinan masyarakat. Di sisi lain, terlalu ketat membatasi ekspresi artistik berpotensi menghambat pertumbuhan industri film nasional.
Posisi proporsional dari lembaga ini perlu ditembuh guna melindungi ruang publik dari representasi yang meresahkan, sembari mengakui film sebagai medium refleksi sosial-agama yang penting bagi masyarakat demokratis. Dengan cara ini, film kontroversial dapat dipahami tidak lagi sebagai hal yang intimidatif, melainkan sebagai peluang untuk memperluas ruang diskusi, memperkaya imajinasi kultural, dan merekonstruksi relasi antara narasi, agama, dan publik di Indonesia kontemporer.